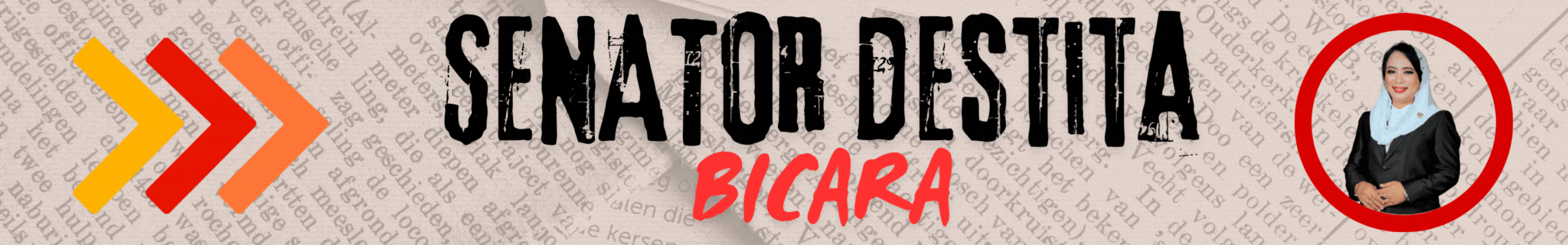Jakarta -Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah langsung mengguncang dinamika demokrasi di Indonesia. Dalam putusan itu, Pemilu Nasional akan meliputi pemilihan Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR RI, dan DPD RI. Sementara Pemilu Daerah mencakup pemilihan Gubernur, Bupati/Wali Kota, serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow mengatakan selama ini, pemilu digelar serentak dalam satu hari dengan lima surat suara sekaligus. Tujuannya: efisiensi, penghematan anggaran, dan penguatan sistem presidensial. Namun dalam praktiknya, pemilu serentak justru menimbulkan beban besar—mulai dari membingungkan pemilih, menumpuk kerja penyelenggara, hingga menyebabkan kelelahan massal yang memakan korban jiwa.
Dengan pemisahan ini, MK seolah ingin membuka jalan baru agar proses pemilu lebih tertata dan berkualitas. Publik bisa fokus pada isu nasional saat memilih Presiden dan parlemen pusat, lalu memberi perhatian khusus pada isu lokal saat memilih kepala daerah dan DPRD. Ini membuka peluang bagi pemilih untuk bersikap lebih rasional dan mendorong peningkatan kualitas demokrasi.
Lebih dari itu, pemisahan ini memberi ruang lebih besar bagi tokoh-tokoh lokal yang punya kapasitas dan rekam jejak baik untuk tampil tanpa harus bergantung pada popularitas calon presiden atau partai besar. Efek coattail—di mana suara calon daerah terdongkrak oleh nama besar capres—bisa ditekan.
Dari sisi teknis, beban kerja KPU, Bawaslu, dan petugas di lapangan juga bisa dibagi. Tidak lagi harus menangani lima surat suara dalam satu waktu, yang selama ini menyulitkan logistik dan membahayakan keselamatan petugas. Dalam jangka panjang, ini bisa menyelamatkan kualitas pelaksanaan pemilu.
Namun, keputusan ini juga menghadirkan tantangan besar.
Pertama, dari sisi anggaran. Dua kali pemilu besar dalam satu siklus lima tahunan berarti biaya dua kali lipat. Negara harus menanggung ongkos logistik, distribusi, pengamanan, dan honor petugas dua kali. Ini bisa jadi beban fiskal, apalagi jika tak diimbangi dengan efisiensi.
Kedua, intensitas politik di masyarakat akan meningkat. Frekuensi ke TPS bertambah. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa memicu kejenuhan atau bahkan apatisme politik. Partisipasi pemilih bisa menurun karena masyarakat lelah dan tak melihat dampak nyata dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.
Ketiga, potensi munculnya politisi “lompat panggung” juga besar. Karena waktu pemilu terpisah, mereka yang gagal di pemilu nasional bisa langsung mencalonkan diri di pemilu daerah, atau sebaliknya. Politik bisa berubah menjadi ajang coba-coba, bukan soal pengabdian. Ini berisiko menyeret demokrasi ke pola pikir jangka pendek dan oportunistik.
Apakah putusan ini baik untuk demokrasi kita?
Jawabannya: bisa ya, bisa juga tidak. Jika dikelola dengan baik, putusan ini bisa menjadi peluang memperbaiki kualitas demokrasi elektoral. Pemilih bisa lebih jernih menilai kandidat, proses lebih tertib, dan tokoh lokal punya ruang lebih luas.
Namun jika tidak disiapkan secara matang—dari regulasi, teknis penyelenggaraan, edukasi publik, partisipasi rakyat, hingga alokasi anggaran—putusan ini bisa menjadi beban baru yang kontraproduktif.
Karena itu, tantangan kita saat ini adalah beradaptasi dengan cepat. Pemerintah, DPR, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat sipil harus bergerak bersama. Revisi regulasi harus segera diselesaikan karena UU Pemilu sedang dibahas. Edukasi publik dan pelibatan masyarakat menjadi kunci agar pemilu tetap inklusif dan demokratis.
Putusan MK ini memang mengejutkan, tapi bersifat final dan mengikat. Apakah ia membawa perbaikan atau menambah masalah, sepenuhnya tergantung pada bagaimana kita merespons dan menyiapkan langkah ke depan. Sebab demokrasi bukan hanya soal hari pencoblosan, tapi soal proses yang dijalankan dengan jujur, adil, efisien, dan berpihak pada rakyat.